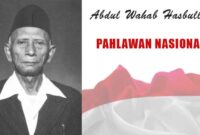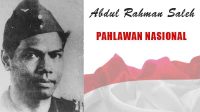Perjalanan Mario Vargas Llaso yang pantang menyerah – Mario Vargas Llaso lahir tanggal 28 Maret 1936 di Arequipa, Peru, lahir dari pasangan Ernesto Vargas Maldonado dan Dora Llosa Ureta. Ia adalah seorang politikus sekaligus novelis pemenang Nobel Sastra tahun 2010 dengan karyanya yang menggambarkan struktur kekuasaan dalam melawan tekanan, perlawanan, pemberontakan, serta kekalahan individu.
Mario telah menulis lebih dari 30 novel, drama, dan esai, termasuk The Feast of the Goat dan The War of the End of the World. Diilhami kekagumannya pada novel-novel tulisan Jules Verne. Sejak kecil ia bercita-cita menjadi penulis. Pada usia 15 tahun, ia sudah bekerja sebagai reporter kriminal.
Orang tua Llosa bercerai sejak ia masih kecil. Ia dibesarkan oleh ibu dan kakeknya yang menjadi konsul Peru di Bolivia. Pada tahun 1946 ia bersama keluarganya kembali ke Peru, di kota kecil Piura. Setelah ayah dan ibunya rujuk kembali, mereka pindah ke Lima.
Saat berumur 14 tahun, ia didaftarkan di Leoncio Prado di Lima ibu kota Peru. Setahun kemudian, ia sudah menjadi reporter paruh waktu di sebuah koran lokal.
Pada usia belasan tahun, Llosa sudah bergabung dengan sel perjuangan komunis. Lalu ia kawin lari dengan Julia Urquidi yang merupakan tantenya sendiri dan sudah berusia 33 tahun. Mereka berdua pergi ke Paris dan di sanalah ia menulis novel.
Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut :
- La Casa Verde (1966/The Green House, 1968)
- Conversacion en La Catedral (1969/Conversation in The Cathedral, 1975)
- Pantaleon y Las Visitadoras (1973/Captain Pantoja and the Special Service, 1978)
Perkawinannya dengan Julia Urquidi tidak bertahan lama. Pada tahun 1965 ia bercerai. Kemudian ia menikahi sepupunya bernama Patricia Llosa yang sepuluh tahun lebih muda dari usianya. Dari perkawinan keduanya ini ia dikaruniai 3 anak.
Selepas kuliah. Llosa menulis untuk berbagai koran di Peru. Ia melanglang ke Paris, Madrid dan London. Pada tahun 1960-an, novelnya yang berjudul The Time of the Hero, yang bertutur tentang kehidupan akademi militer di Peru mulai disambut hangat oleh publik pembaca dunia, namun di dalam negeri memicu kontroversi.
Pada tahun 1970-an, ia mengecam pemerintahan Kuba di bawah kendali Fidel Castro, serta perlahan-lahan menunjukkan perubahan haluan ke arah konservatisme pasar bebas. Perubahan sikap ini memicu perdebatan sengit dengan para sastrawan kontemporer Amerika Latin, tak terkecuali dengan karibnya, Gabriel Garcia Marquez.
Saat Peru dihajar inflasi tinggi dan serentetan serangan berdarah oleh pemberontak Shining Path yang berhaluan Maois pada tahun 1990, Llosa mencalonkan diri sebagai presiden melawan Alberto Fujimori. Ia mengusung ide-ide perekonomian berorientasi pasar dalam kampanye dan unggul di berbagai poling prapemilihan.
Namun, ia kalah ketika pemilihan berlangsung. Kekalahan tersebut disinyalir karena penampilannya yang cenderung aristokrat di tengah mayoritas penduduk miskin dan pengakuannya bahwa dirinya agnostik di negeri yang berpenduduk mayoritas penganut Katolik Roma.
Ide Progresifnya tentang orientasi pasar diterapkan oleh Fujimori, rival politiknya dan ternyata berhasil menciptakan stabilitas ekonomi di Peru kala itu.
Kekalahannya dalam perebutan kursi presiden tak lantas membuat semangat Llosa surut, tetapi justru membawa berkah baginya. Ia terus berkarya dan menghasilkan banyak karangan yang luar biasa. Karyanya yang banyak memotret dunia perpolitikan mendapatkan penghargaan Hadiah Nobel Sastra.
Sosok yang gagal menjadi politisi, akhirnya disadarkan bahwa jalan kepenulisan lebih mematangkan dirinya. Kegagalannya berpolitik membuatnya terpacu untuk terus menghasilkan karya sastra yang lebih baik.
Baca juga: Konsistensi tema politik dalam karya Llosa
Dari perjalanan Mario Vargas Llaso tersebut dapat kita jadikan motivasi, bahwa suatu kegagalan jangan lantas diterima dengan keputusasaan. Tuhan lebih tahu bagaimana, dimana, dan bagaimana memposisikan umat-Nya agar lebih baik.